| Posisi Mistisisme (Irfan) dalam Hirarki Ilmu-ilmu Islam |  |  |
| Ditulis Oleh Muhsin Araki | |
| Jumaat, 09 Mei 2008 | |
| Untuk menegaskan dan mendefinisikan lokasi yang tepat bagi penelitian mistisisme, kami perlu menjelaskan tiga isu kontekstual. Pertama, apa yang dimaksud dengan istilah “ilmu-ilmu Islam?” Kedua, apa karakteristik yang sama dan apa yang membedakan mistisisme dari jenis sains dan disiplin ilmu Islam yang lain? Ketiga, bagaimana mistisisme berkembang dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain, dan bagaimana mereka ini saling mempengaruhi? Suatu Definisi Umum tentang Ilmu-ilmu Islam Ilmu-ilmu Islam (ulum islamiyyah) merupakan konsep yang digunakan dalam dua makna.1 Makna yang pertama dipahami secara luas. Ilmu-ilmu Islam, dalam maknanya yang luas, meliputi suatu konstelasi berbagai disiplin ilmu, yang telah terlibat dalam konteks peradaban Islam, baik yang berkembang dari sumber-sumber dan prinsip-prinsip Islam maupun yang telah ada dalam komunitas dan peradaban lain (ulum al-awa’il), tetapi terintegrasi dan berkembang di dalam peradaban Islam. Ilmu-ilmu Islam dalam makna luas ini merangkul berbagai disiplin ilmu yang lazim diyakini oleh para ilmuwan Islam di berbagai institusi ilmiah dan akademis di dunia Islam di sepanjang sejarah Islam. Konsekuensinya, baik ilmu-ilmu Islam seperti fikih, teologi, ushul fikih, tafsir al-Quran, dan sejarah hidup (sirah) Nabi saw dan para imam maksum as, dan ilmu-ilmu yang lain yang berasal dari peradaban lain seperti astronomi, obat-obatan, dan matematika, semuanya sesuai dengan kategori yang luas ini. Makna yang kedua lebih sempit. Definisi sempit ini meliputi disiplin-disiplin ilmu yang langsung berasal dari prinsip-prinsip dan sumber-sumber Islam, yaitu al-Quran, hadis (sunah) Nabi saw dan para imam as, dan keketapan-ketetapan yang berasal dari al-Quran. Kategori ilmu-ilmu ini merupakan inovasi umat Islam, dan sebenarnya, merupakan sebuah ilustrasi dan interpretasi dari hadis Nabi saw. Kategori yang sempit dari ilmu-ilmu Islam itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama meliputi ilmu-ilmu yang dikembangkan semata-mata untuk tujuan penafsiran dan penjabaran makna dan tujuan al-Quran dan hadis Nabi saw. Yang kedua meliputi ilmu-ilmu yang dianggap sebagai suatu pengantar pada kelompok yang pertama, misalnya logika, literatur dan tata bahasa Arab, sejarah Islam, rujukan-rujukan yang berkaitan dengan pemahaman al-Quran, dan ilmu pembacaan al-Quran, dan ilmu untuk melakukan verifikasi periwayat hadis Nabi saw dan para imam as (ilm ar-rijal). Ilmu-ilmu Islam juga dibagi menjadi dua kategori berdasarkan metodologinya. Mereka bisa didasarkan pada penalaran murni, bisa pula memperoleh otoritasnya dari sumber-sumber agama. Kategori yang pertama, yang didasarkan pada investigasi intelektual, meliputi ilmu-ilmu intelektual (ulum al-aqliyyah). Yang kedua meliputi ilmu-ilmu yang didasarkan pada otoritas dan penafsiran terhadap kitab suci (ulum an-naqliyyah). Dalam ilmu-ilmu yang berasal dari kitab suci —skriptural, otoritas sumber-sumber yang suci ini merupakan landasan utama argumentasi-argumentasinya. Namun demikian, derajat penalaran rasional dalam ilmu-ilmu ini bervariasi. Disiplin-disiplin ilmu seperti filsafat (falsafah al-Ilahiyyah), mistisisme teoritis, logika, dan teologi rasional (kalam al-aqli) hanya menggunakan premis-premis rasional dalam argumentasi mereka. Jelas, bahwa mereka masuk ke dalam kategori yang pertama; sedangkan mistisisme praktis teologi skriptural, ushul fikih dan penafsiran al-Quran, dianggap sebagai ilmu-ilmu skriptural. Kesamaan dan Perbedaan antara Mistisisme dan Cabang-cabang Lain Ilmu-ilmu Islam Ilmu-ilmu Islam berbeda dalam bahasannya, tujuan atau metodologinya, atau salah satu atau dua dari faktor-faktor ini. Misalnya, teologi berbeda dari fikih dari sisi bahasan dan tujuannya. Bahasan teologi adalah sikap religius seseorang terhadap umat manusia dan dunia, sedangkan bahasan fikih adalah aktivitas manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia lain, dan dunia. Tujuan teologi adalah mencapai kedamaian pikiran dan kepastian dalam sebuah dunia yang tidak pasti, sedangkan fikih berurusan dengan kesesuaian tindakan-tindakan kita dengan perintah-perintah Tuhan. Di sisi lain, tidak seperti fikih, teologi rasional mengikuti suatu metodologi rasional dan kebanyakan hanya mengandalkan “nalar—akal” (aql), sedangkan teologi skriptural memiliki metodologi yang sama dengan fikih, dengan mengombinasikan metodologi argumentasi skriptural dan akal murni. Filsafat Islam (metafisika) dan teologi juga berbeda dalam hal bahasan dan tujuannya. Bahasan metafisika adalah eksistensi murni (al-wujud bima huwa wujud), sedangkan bahasan teologi adalah eksistensi Tuhan (kesadaran atas eksistensi-Nya adalah wajib). Namun demikian, kedua disiplin ilmu ini menggunakan metodologi yang sama dalam mencapai tujuan mereka, yakni akal murni. Maksud kami di sini adalah memperlihatkan kesamaan dan perbedaan antara mistisisme dan disiplin-disiplin lain dalam ilmu Islam. Kategorisasi ilmu-ilmu Islam ke dalam ilmu pengantar dan ilmu inti menempatkan mistisisme ke dalam kategori inti dan fundamental. Ia juga masuk ke dalam kategori ilmu rasional, walaupun mistisisme praktis masuk ke dalam kategori ilmu-ilmu skriptural. Masuknya mistisisme teoritis ke dalam ilmu-ilmu intelektual menunjukkan bahwa mistisisme tipe ini mendorong penemuan intuisi melalui penalaran rasional, walaupun sumber utama intuisi dan pengetahuan diperoleh melalui penyucian hati. Hasil-hasil perjalanan spiritual seperti itu seringkali ditegaskan oleh penalaran induktif. Sebagai hasil dari sebuah metodologi yang diperluas seperti itu, kita bisa mengklasifikasikan tipe pengetahuan ini sebagai bagian dari ilmu-ilmu rasional. Salah satu prinsip utama dari disiplin ilmu ini, yang disepakati oleh semua ulama irfan, adalah bahwa orang harus mengikuti seorang pembimbing dalam semua tahap perjalanan spiritual. Pemimpin yang jujur dan berpengalaman, yang dipilih sebagai pembimbing dalam perjalanan ini harus juga seorang kekasih Tuhan (wali Allah).2 Guru dan pembimbing yang terbesar dalam perjalanan spiritual kepada Tuhan adalah Nabi Islam, Muhammad saw. Beliau dan keturunannya adalah para guru dan pembimbing terbesar yang harus diikuti oleh manusia dalam pencarian spiritualnya atas kebenaran dan makna kehidupan. Mereka adalah orang-orang terdepan dalam pengetahuan dan para guru cinta, dan tanpa mereka manusia bisa tersesat, karena upaya yang dilakukannya itu bisa berubah menjadi perjalanan yang sangat beresiko tanpa bimbingan para wali Tuhan ini. Interpretasi ini berdasarkan pemikiran Syiah yang menempatkan akal sebagai bagian utama. Rujukan kepada suatu otoritas, dalam pemikiran Syiah dianggap tidak meyakinkan. Pada analisis akhirnya, otoritas terletak pada akal. Di sisi lain, beberapa mahzab pemikiran, terutama dari kalangan mahzab Islam Suni, menisbatkan otoritas absolut kepada Nabi saw dan menolak peran akal. Perlunya memiliki seorang tutor dalam jalan spiritual telah dikatakan berulang kali oleh para guru besar di bidang ini. Jalaluddin Rumi (w. 1274), guru besar sufi dan pendiri Ordo Maulawi yang beranggotakan para darwis, dalam risalahnya yang sangat menarik, Mathnavi-ye Ma‘navi, mengingatkan kita tentang pentingnya hal tersebut, ketika ia berkata: Ikutilah sang guru (pir) karena tanpanya, perjalanan ini sangat penuh bahaya Karena itu, di jalan yang belum kau lihat sebelumnya Hendaknya kau tak pergi sendiri, jangan membantah sang pembimbing3 Hafizh(w. 1389), ahli lain dalam bidang ini menyatakan hal yang sama ketika ia berkata: Janganlah berjalan ke wilayah cinta tanpa alasan yang kuat, Aku telah melakukan ratusan upaya namun sia-sia Waspadalah dengan jalan yang penuh bahaya ini tanpa bimbingan Khidir, ia adalah kegelapan, dan bahaya tersesat pun hadir. Menurut prinsip irfan yang penting ini, adalah wajib untuk mengikuti seorang kekasih atau wakil Tuhan. Mengikuti Nabi Suci saw dan orang-orang yang paling dekat dengannya sebagai kekasih Tuhan adalah hal yang paling penting. Kedua, mereka yang paling akrab dengan praktik dan ajaran Nabi saw dan para imam as juga ditunjuk untuk membimbing manusia. Perbedaan antara Problem Filsafat dengan Problem Irfan Ketentuan untuk mengikuti Nabi saw dan para wali yang lain mengisyaratkan bahwa irfan praktis adalah suatu ilmu yang didasarkan pada otoritas skriptural. Manusia hanya boleh mengikuti mereka melalui suatu pemahaman terhadap tindakan mereka dan terhadap al-Quran. Namun demikian, mistisisme, filsafat, dan teologi teoritis memiliki karakteristik lazim yang sama seperti inkuiri intelektual pada sifat eksistensi. Di sisi lain, irfan praktis ini serupa dengan etika dan fikih, karena ketiganya berurusan dengan masyarakat manusia. Ilmu-ilmu Islam yang lain tidak memiliki landasan yang sama dengan irfan, sehingga tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Karakteristik-karakteristik disiplin ilmu mana pun terdiri dari dari empat elemen. Pertama, metodologi menetapkan model-model inkuiri dan metoda verifikasi; kedua, pokok bahasan (mawdhu)mendefinisikan ilmu, karena suatu “ilmu meneliti kelengkapan esensial dari pokok bahasannya”;4 ketiga, apriori dan topik(masa’il, qadhayah) yang terlibat turut menentukan karakteristik disiplin ilmu tersebut; keempat, tujuan dan telos(ghayah) dari suatu ilmu mendefinisikan tujuan penelitian.5 Irfan teoritis menggunakan sebuah metodologi yang berbeda dari yang digunakan oleh filsafat dan teologi. Selain suatu metodologi intelektual, ia terutama mengandalkan pada intuisi (isyraq) dan pengalaman langsung (dzawq). Ilmu ini lebih memilih pengetahuan yang diilhami oleh suatu pemahaman melalui hati, daripada yang melalui penalaran logis. Karena melalui intuisi, suatu penyatuan antara subjek pengetahuan, pengetahuan itu sendiri, dan yang memiliki pengetahuan terjadi (ittihad al-aql wa al-aqil wa al-ma‘qul). Sebaliknya, hasil-hasil penelitian rasional hanya beberapa refleksi atau image kognitif dari pokok bahasannya, dan realitas dari pokok bahasannya sendiri tidak hadir pada orang yang memiliki pengetahuan tersebut. Mistisisme teoritis dan teologi adalah sama, karena keduanya menetapkan hasil-hasilnya sebelum penalaran apa pun, dan kemudian mencoba untuk memperkuatnya melalui penalaran. Namun demikian, keduanya berbeda karena dasar suatu pengetahuan priori dalam teologi memiliki otoritas religius, dan dalam irfan teoritis, pengetahuan diperoleh melalui intuisi. Berkaitan dengan pokok bahasannya, filsafat berbeda dengan irfan teoritis. Bahasan filsafat adalah eksistensi murni atau eksistensi qua eksistensi. Bahasan irfan teoritis, sebaliknya, adalah Tuhan atau suatu model eksistensi, yang ketiadaannya adalah hal yang secara logis mustahil dibayangkan, yakni Eksisten Wajib (wajib al-wujud). Filsafat berurusan dengan eksistensi dalam bentuk dan sifat-sifatnya yang murni, tanpa memandang tipe eksistensinya. Namun demikian, mistisisme hanya berfokus kepada Tuhan dan eksistensi-Nya, karena bentuk-bentuk eksisten lain itu sebenarnya tidak ada; mereka hanyalah sebuah bayangan eksistensi, yakni eksistensi Tuhan.6 Dia adalah eksistensi dan segala sesuatu yang lain merupakan sebuah bayangan dari eksistensi-Nya. Menurut irfan, eksistensi itu ekuivalen dengan wajibnya eksistensi. Artinya bahwa eksistensi yang sejati adalah yang secara mutlak wajib ada, yaitu Tuhan. Yang lainnya memiliki suatu eksistensi yang bersifat ilusi. Bahasan teologi menyertakan isu-isu yang berkenaan dengan asal-usul penciptaan, kebangkitan, kenabian, kepemimpinan, dan topik-topik terkait. Eksistensi Tuhan dan sifat-sifat-Nya merupakan bahasan mistisisme. Namun demikian, mistisisme tidak berurusan dengan pembuktian adanya Tuhan, yang di luar cakupannya. Tidak ada disiplin ilmu yang diperlukan untuk membuktikan eksistensi pokok bahasannya. Eksistensi Tuhan tidak memperoleh perhatian dalam mistisisme, dan tugas onto-teologi atau teologilah untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Sekedar fakta bahwa Tuhan itu ada adalah masalah filosofis, karena sifat wajib ada di antara sifat-sifat eksistensi. Konsepsi umum dalam mistisisme dan filsafat tidak sama. Dalam filsafat, eksistensi dibagi menjadi kategori-kategori semacam: kejamakan dan ketunggalan, kausalitas, esensi dan sifat-sifat, keabadian dan sifat baru, dan eksistensi wajib (inheren) atau eksistensi yang mungkin. Namun demikian, dalam mistisisme dengan asumsinya tentang monorealisme (wahdat al-wujud), kategori-kategori eksistensi ini sama sekali tidak masuk akal. Berbagai bentuk dan warna berbeda pada eksisten adalah ilusi, karena ada ketunggalan dalam ketunggalan. Yang ada hanya satu realitas. Dalam filsafat, yang dipertimbangkan adalah konsep-konsep umum. Melalui sebuah proses abstraksi deduktif, pikiran melanjutkan untuk mengonseptualisasikan beberapa konsep umum, yang tidak memiliki posisi dalam eksistensi konkrit. Tahap pertama proses semacam itu terjadi dengan membentuk sebuah konsep umum, yang bisa diterapkan para subjek-subjek yang aktual dan nyata. Misalnya, konsep tentang “kucing” diasumsikan dari seekor atau banyak kucing yang nyata, tetapi konsep umum ini tidak ekuivalen dengan bayangan kita tentang kucing individual mana pun. Ini merupakan sebuah konsep umum, yang meliputi sifat-sifat lazim kucing, dan mengabaikan perbedaannya. Konseptualisasi ini bahkan bisa melangkah lebih jauh dan menghasilkan konsep sekunder, seperti seekor “binatang.” Bahkan ada sebuah konseptualisasi yang lebih canggih ketika kita menyimpulkan kategori-kategori logis seperti “generality-sifat umum,” “necessity-sifat wajib,” “causality-kausalitas” dan sebagainya. Mereka bisa berupa konsep sekunder yang logis atau yang filosofis (ma‘qulat tsaniyyah manthiqiyyah aw falsafiyyah). Shadruddin Muhammad Syirazi (w. 1641) dikenal sebagai Mulla Shadra, seorang filosof zaman kebangkitan Safawi di Iran, mengakhiri kontroversi antara filsafat dan irfan ketika ia memperkenalkan filsafat transendentalnya, dengan menggabungkan elemen-elemen dari kedua belah pihak.7 Nilai orisinal kontribusinya terletak pada teori eksistensialisnya (jangan terkacaukan dengan eksistensialisme Eropa Modern),8 yang menurutnya, batas-batas eksistensi yang membentuk identitas sesuatu dianggap sebagai hal yang sekunder pada eksistensi itu sendiri. Dalam teori piramida eksistensi (hiram-e hasti)-nya, semua makhluk memiliki eksistensi, namun perbedaan mereka berasal dari derajat atau intensitas eksistensi mereka. Eksistensi Tuhan dalam piramida ini tidak memiliki batasan dan keterbatasan. Oleh karena itu, identitasnya identik dengan eksistensi-Nya. Dengan pemahaman seperti ini, perbedaan antara filsafat dengan irfan bisa diselesaikan. Ada kejamakan (derajat eksistensi) dalam ketunggalan (semua wujud memiliki eksistensi).9 Ini merupakan doktrin tasykik al-wujid, atau gradasi dan modulasi eksistensi.10 Sifat Konstan Eksistensi Apakah eksistensi itu statis atau dinamis? Jika dinamis, bagaimana ia bisa konstan dan berkelanjutan? Jika eksistensi itu konstan, apa pengaruhnya bagi pikiran? Para filosof Islam klasik percaya bahwa jika suatu wujud ciptaan dan penyebab eksistensinya itu ada, maka wujud itu akan terus ada, tak terpengaruh oleh berlalunya waktu. Sebenarnya, mereka berpikir bahwa alih-alih berlalunya waktu, wujud tetap mempertahankan identitasnya (huwiyyah). Mistisisme tidak sepakat dengan pemikiran ini. Dalam irfan, tidak ada keberlangsungan seperti itu, dan eksistensi diperbarui secara konstan. Mereka memiliki identitas baru seiring dengan berjalannya waktu. Imajinasi kitalah yang berusaha untuk mengabaikan transformasi fundamental ini. Karenanya, eksistensi itu adalah sebuah proses untuk menjadi —process of becoming. Ketidakcocokan antara pendekatan filosofis dan mistis ini diselesaikan oleh Mulla Shadra melalui teori gerak substansial (harakah jawhariyyah). Dia berpendapat bahwa walaupun eksistensi cair menjalani perubahan yang konstan, ada satu faktor yang selalu menyertai eksistensi yang mengalir jauh ini di sepanjang waktu. Ia adalah eksistensi itu sendiri, yang senantiasa hadir pada setiap detik dari segala perubahan. Sekali lagi, aspek statis dan dinamis yang dimiliki eksistensi bisa dipertemukan.[] Catatan: 1. Tentang hirarki pengetahuan, lihat Seyed Hossein Nasr, Science and Civilization in Islam, edisi ke-2, Cambridge: Islamic Texts Society 1987, hal.59-64; Osman Bakar, The Classification of the Sciences in Islamic Philosophy, Cambridge: Islamic Texts Society 2000. 2. Tentang tema penting ini, lihat Allamah Thabathaba’i, Risalat al-Wilaya, Tehran: Intisharat-e Hikmat 1374 Syamsi, dan Hasan Zadah Amuli, "Vilayat-e Takvini," dalam Majma‘a-ye Maqalat, Qum: Daftar-e Tablighat-e Islami 1375 Syamsi, hal.31-82. 3. Rumi, Mathnavi-ye Ma‘navi, ed. R.A. Nicholson, London: Gibb Memorial Trust 1925-40, vol.II, ayat ke-2943. 4. Bandingkan dengan Katibi Qazwini, “al-Risalah al-Syamsiyyah” dalam Biblioteca Indica Appendix I, ed. A. Sprenger, Calcutta: Bengal Military Orphan Press 1854, hal.3. 5. Skema empat lapis ini memiliki para pendahulu terkemuka di zaman Neoplatonis dan penyusunan kurikulum dan pendidikan tradisional. Lihat, I. Hadot, "Les introductions aux commentaires exégètiques," dalam Les règles de l’interpretation, ed. M. Tardieu, Paris: Presses Universitaires de France 1987, hal.99-122. 6. Dawud Qaysari, Syarh-e Muqaddima-ye Qaysari bar Fushush al-Hikam, ed. S.J. ashtiyânî, Qum: Daftar-e Tablighat-e Islami 1991, hal.100. 7. Dalam beberapa tulisannya, dia lebih mengistimewakan mistisisme daripada filsafat. Misalnya, dalam hirarki ilmunya dalam “Iksir al-‘Arifin” dalam Rasa’il, Tehran lithograph 1885, hal.279-86, dia menempatkan ilmu-ilmu “kondisi” (ahwal) pada puncak pencarian akal. Filsafat lain yang menempatkan mistisisme sebagai kulminasi pencarian adalah Quthbuddin Syirazi (w. 1311), yang melengkapi ensiklopedinya, Durrat al-Taj li-Ghurrat al-Dubaj dengan sebuah khatima tentang mistisisme —lihat, Majlis-e Syura 4720, vol.596-620; bandingkan dengan J. Walbridge, "A Sufi scientist of the thirteenth century: The mystical ideas and practices of Quthbuddin Syirazi," dalam The heritage of Sufism Volume II: The Legacy of Medieval Persian Sufism, ed. L. Lewisohn, laporan, Oxford: Oneworld 1999, hal.326-40. 8. Bandingkan dengan diskusi pembuka Henry Corbin dalam pendahuluannya pada Mulla Shadra Syirazi, Kitab al-Masha‘ir (Le Livre des Pénétrations Métaphysiques, laporan,Tehran 1982, hal.62-75. 9. Lihat Fazlurrahman, The philosophy of Mulla Shadra, Albany: State University of New York Press 1975, hal.27-41. 10. Lihat Sajjad H. Rizvi, Modulation of Being (Tasykik al-Wujud) in the Philosophy of Mulla Shadra Syirazi, desertasi doktoral yang tidak dipublikasikan, Cambridge University 2000. |


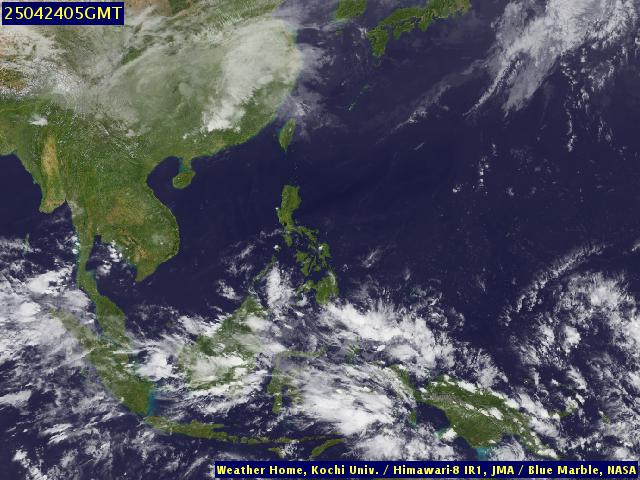
No comments:
Post a Comment