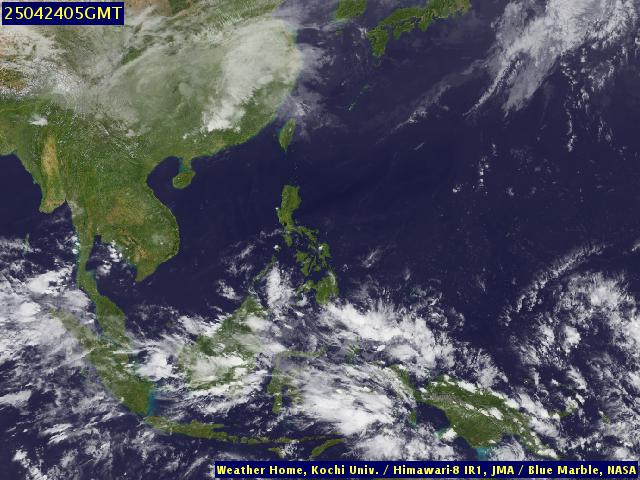LOGIKA IJITIHAD:
Definisi dan perkembangannya dalam khazanah pemikiran islam
Saleh Lapadi
Berbicara mengenai ijtihad memang menarik. Ijtihad salah satu sumber inspirasi guna memacu islam menyesuaikan dirinya dengan percepatan zaman. Tanpa ijtihad sama artinya mengembalikan kehidupan era millenium ini sesuai dengan seribu empat ratus tahun lalu. Mungkin umat islam perlu memikirkan unta (lagi) sebagai ganti mobil dan kereta api selain sebagai alat transport yang ramah lingkungan juga sesuai dengan sunnah nabi yang senantiasa hilir mudik dengannya[1].
Ijtihad juga merupakan satu kata kunci guna dapat memahami islam. Mengingat proses ijtihad membutuhkan kemampuan komprehensif seorang pemikir islam (baca: mujtahid) atas ilmu-ilmu islam dan tentunya ilmu-ilmu lain dan metodologi yang memiliki kaitan erat dalam proses penyimpulan sebuah hukum syareat.
Sayangnya, usaha memperbaharui pemahaman islam (dengan tanpa melupakan usaha yang telah dilakukan) kemudian menjadi terbalik. Dengan slogan yang sama yaitu meneruskan tradisi ijtihad dengan penguasaan yang baik terhadap ilmu-ilmu dan metodologi yang berkembang sekarang namun dengan kemampuan ilmu-ilmu islam yang tidak sebanding. Fenomena ini memang berbanding terbalik dengan mayoritas ulama sebelumnya yang minim akan ilmu-ilmu dan metodologi yang dapat mendongkrak kualitas hasil penyimpulan hukumnya. Walaupun hal ini masih ditolerir mengingat perkembangan metodologi di dunia barat lebih dahulu terjadi.
Kondisi ini semakin diperburuk dengan kurangnya informasi seorang pemikir islam mengenai aliran-aliran pemikiran dalam islam. Tarik saja dari masalah ushuluddin hingga furu’uddin. Ini sering tidak menjadi fokus perhatian mereka yang ingin mengkaji sesuatu dan akan mengatasnamakan kajiannya sebagai pandangan islam. Katakanlah bahwa pemetaan perbedaan pemikiran telah dilakukan, hal yang masih harus dipertanyakan adalah informasi perbedaan tersebut lebih sering bukan dari sumber-sumber pertama. Selain secara ilmiah hal masih perlu dipertanyakan, akan semakin ruwet lagi bila penukilan tersebut jatuh ke tangan mereka yang membenci pemikiran lain[2].
Akhirnya, alih-alih ijtihad membawa cakrawala baru bahkan menambah pekerjaan rumah yang telah menumpuk. Kenyataan ini menuntut sebuah langkah serius untuk membenahi dan menata kembali pranata ijtihad. Banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan ijtihad yang selama ini jangankan dikaji dilirik pun tidak pernah. Sebagai contoh, apakah Allah memiliki hukum-hukum selain yang termaktub di al-Quran dan hadis? Bila jawabannya adalah “tidak” maka ketika seorang pemikir islam menyampaikan sebuah hukum sebagai hasil dari ijtihadnya, apa esensi hukum yang dihasilkannya? Apakah setara dengan al-Quran dan hadis ataukah tidak ? Seberapa besar kebenaran yang dikandungnya? Dengan kata lain, proses ijtihad dan hasilnya lebih memiliki sosok manusiawi dari pada ilahi, hukum yang dihasilkan memang tidak punya kaitan dengan Allah, dan lain-lain. Bila jawabannya adalah ‘iya’ proses yang dilakukan dalam ijtihad adalah menyingkap hukum Allah. Pertanyaannya adalah seberapa jauh urgensi seorang pemikir islam harus melakukan ijtihad? Hukum yang dihasilkannya, karena tidak termaktub dalam al-Quran dan hadis, disebut apa? Apa esensinya? Di sini proses ijtihad tidak murni manusiawi karena kesimpulan akhir yang ingin diraih adalah menyingkap hukum Allah. Dan masih banyak lagi pertanyaan seputar ijtihad yang belum digali.
Ijtihad sendiri dalam perkembangan maknanya tidaklah sesederhana yang dibayangkan selama ini. Kata ijtihad sendiri pernah menjadi biang sengketa yang sempat membuat Syiah tidak memakai kata ini. Hal itu karena Ahli Sunah menggunakannya dengan sebuah pemaknaan khusus. Para Imam Syiah dalam banyak hadis mengisyaratkan bahwa ijtihad yang dilakukan oleh ulama Ahli Sunah adalah batil. Hal itu diikuti oleh ulama Syiah dengan menulis buku-buku yang intinya menolak ijtihad. Artinya, ijtihad sempat mendapat penilaian miring.
Ijtihad untuk kedua kalinya, dalam Syiah, mendapat kritikan-kritikan tajam oleh ulama yang mengatasnamakan dirinya Akhbariyun berhadap-hadapan dengan Ushuliyun[3]. Ahli Sunah yang sebelumnya adalah lokomotif gerbong gerakan ijtihad harus menelan pil pahit dengan tertutupnya pintu ijtihad.
Definisi ijtihad
Sebagaimana kata-kata kunci lainnya dalam islam, ijtihad adalah bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Sekalipun kamus-kamus bahasa Indonesia telah memaknainya namun hal itu tidak cukup untuk menjelaskan hakikat ijtihad itu sendiri. Perlu kajian khusus berkenaan dengannya guna menemukan arti yang sesungguhnya yang pada gilirannya kajian seputar ijtihad tidak lagi mengambang. Mengapa? Hal itu tidak lain dikarenakan beberapa pertanyaan sekaitan dengan ijtihad dengan sendirinya akan ditemukan jawabannya setelah maknanya menjadi jelas.
Kata ijtihad dalam bahasa Arab mengambil bentuk masdar tsulatsi mazid[4]. Bila dikembalikan ke bentuk aslinya yang hanya memiliki tiga huruf ia menjadi jahada dan bentuk masdarnya ada dua; jahdun dan juhdun. Para ahli bahasa terbagi dalam pemaknaan dua kata ini. Ada yang menganggap keduanya memiliki satu arti sedangkan yang lainya meyakini masing-masing memiliki arti sendiri-sendiri.
Jauhari menuliskan: “Al-Jahdu dan al-Juhdu kedua-duanya memiliki arti kemampuan, oleh karenanya pada surat Taubah ayat 79 dapat dibaca kedua-duanya, Walladzina laa yajiduna illa jahdahum atau juhdahum.
Sementara Ahmad Fayyumi dalam kamusnya membedakan antara al-Jahdu dan al-Juhdu. Ia menuliskan: “Al-Juhd adalah kata yang dipakai oleh orang-orang Hijaz sementara kata al-Jahd dipakai oleh selain Arab Hijaz. Al-Jahd memiliki arti mengerahkan segenap kemampuan. Sementara kata al-Juhd mengandung makna kesulitan[6].
Mencermati arti yang disampaikan para ahli bahasa terlihat ada perbedaan dalam memaknai akar kata ijtihad. Namun bila diteliti lebih dalam lagi sebenarnya tidak ada perbedaan di sana. Kata al-Jahdu yang memiliki arti mengerahkan segenap kemampuan tidak akan pernah dilakukan oleh seseorang bila tidak menemui sebuah kesulitan. Artinya kedua kata ini saling melengkapi. Setiap kesulitan akan dihadapi dengan segenap kekuatan yang dimiliki sebagaimana segenap kekuatan hanya akan dikeluarkan bila menghadapi kesulitan.
Raghib Al Isfahani dengan indah mengartikan kata ijtihad dengan menggabungkan dua unsur tersebut. Beliau menuliskan, ‘Wa Al Ijtihadu Akhdzun Nafsi Bi Badzlit Thoqoti Wa Tahammuli Al Masyaqqoh’ (Ijtihad adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan segala kemampuan yang dimiliki dan menanggung semua kesulitan yang ada)[7].
Ijtihad dalam riwayat
Pada bab ‘Kaifa As Sholah ‘Alan Nabiyi Shollallaahu ‘alaihi wa sallam’ An-Nasa’i meriwayatkan bahwa Zaid bin Kharijah berkata: “Aku mendengar Rasulullah berkata, Ucapakanlah shalawat kepadaku, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk berdoa dan katakan, Allohumma Sholli ‘Ala Muhammad Wa Ali Muhammad”’[8].
Imam Ali as berkata: “Alhamdulillahi alladzi laa yablughu midhatahu alqooilun, … wa laa yuaddi haqqohu almujtahidun, …” (segala puji bagi Allah, tidak akan pernah mampu orang memujiNya dengan sebenar-benar pujian, …, dan usaha sebesar apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha tidak akan pernah setara dengan hak yang dimilikinya atas hambaNya[9].
Tsiqotul Islam Kulaini membawakan sebuah hadis dari Imam Shadiq as pada bab “Haq Al Mukmin ‘Ala Akhiihi Wa Ada’u Haqqihi” (hak seorang mukmin atas saudara mukminnya dan menunaikan haknya) yang berbunyi: “Al muslimu akhu al muslimi laa yuzlimuhu wa laa yakhdzuluhu wa laa yakhunuhu wa yahiqqu ‘ala al muslimina al ijtihadu fi at tawasshuli wa at ta’awuni’ala at ta’atufi wa almusawati li ahli al hajati” (sesama muslim diikat oleh tali persaudaraan, ia tidak menganiaya saudaranya, tidak membiarkannya, tidak mengkhianatinya. Seyogianya seorang muslim berusaha sungguh-sungguh untuk menyambung silaturahmi dengan saudaranya, saling membantu, saling menyayangi, bersama-sama mengulurkan tangan membantu orang yang membutuhkan pertolongan)[10].
Aisyah ra istri Nabi sempat mengomentari perilaku Rasulullah ketika memasuki bulan Ramadhan. Ibnu Majah menukilkan dari Aisyah ra: “Nabi senantiasa berusaha lebih giat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah ketika memasuki hari-hari kesepuluh terakhir dari bulan Ramadhan berbeda dengan hari-hari selainnya”[11].
Riwayat-riwayat di atas menegaskan pemakaian kata ijtihad oleh Nabi dan yang lainnya sesuai dengan makna yang dituliskan oleh para pakar bahasa Arab.
Terminologi ijtihad dalam islam
Pakar-pakar bahasa Arab dengan gamblang menjelaskan arti kata ijtihad dalam kamus-kamus mereka. Sementara untuk menjelaskan terminologi ijtihad dalam islam ada sedikit masalah. Hal itu dikarenakan kata ijtihad dalam perkembangan maknanya tidak sebagaimana yang dibayangkan selama ini karena ia mengalami dua fase pemaknaan. Dua bentuk pemaknaan kata ijtihad inilah yang sempat menjadi titik api mengapa Syiah menolak ijtihad.
1. Ijtihad dengan makna khusus
Mendefinisikan ijtihad dengan makna khusus bukanlah hal yang mudah. Hal itu lebih disebabkan karena ulama Ahli Sunah ketika mencoba mendefinisikannya tidak dengan ungkapan yang satu tapi berbeda-beda.
Muhammad bin Idris as-Syafi’i ra adalah orang pertama yang berusaha mendefinisikan kata ijtihad dalam bukunya ar-Risalah[12]. Bahkan satu-satunya dari empat mazhab Ahli Sunah yang memiliki peninggalan buku-buku fiqih dan ushul fiqih. Beliau dalam ar-Risalahnya ada bab yang judulnya Qiyas, Ijtihad, Istihsan dan Ikhtilaf. Pada bab Qiyas ditanyakan: “Apa itu qiyas, apakah Qiyas sama dengan ijtihad ataukah keduanya adalah kata yang memiliki arti berbeda?” Aku (Syafi’i) menjawab: “Kedua adalah dua kata untuk satu makna”[13].
Menjadi orang pertama yang mendefinisikan kata ijtihad tidak berarti Imam Syafi’i menjadi orang pertama yang mempergunakan qiyas. Abu Hanifah, sebagai penggagas mazhab Hanafiyah, yang memopulerkan penggunaan qiyas. Hal itu dapat dimaklumi mengingat mazhab yang dikembangkannya disebut dengan madrasah ra’yu.
Ensiklopedia fiqih islam yang dikenal dengan nama Mausu’ah Fiqh Jamal Abdun Naser’(Ensiklopedia Fiqih Jamal Abdun Naser), pada pasal Anwa’ Ijtihad (bentuk-bentuk ijtihad), setelah menjelaskan makna ijtihad dalam arti yang umum, memerikan apa arti ijtihad khusus. Disebutkan: “Kedua, ijtihad lewat pemikiran pribadi. Ijtihad yang dilakukan ketika tidak ditemukan teks-teks Al-Quran dan hadis juga tidak ada ijma’ berkenaan dengan sebuah masalah. Demikian pula mencakup proses penyimpulan sebuah hukum syar’i dengan memakai kaedah-kaedah umum syareat. Ijtihad yang semacam ini disebut Ijtihad Ra’yu”[14].
Muhammad Salam Madkur menggambarkan sikap para sahabat sekaitan dengan masalah ijtihad tidak hanya melakukan qiyas tapi juga mencakup Ijtihad Ra’yu, Mashalih Mursalah dan Istihsan. Beliau menulis: “Ijtihad para sahabat Nabi ada tiga bentuk. Pertama, penjelasan teks-teks syar’i dan penafsirannya. Kedua, mengqiyaskan masalah dengan teks-teks syar’i dan ijma’. Ketiga, Ijtihad Ra’yu, Mashalih Mursalah, Istihsan. Kelompok ketiga inilah yang sering dilakukan oleh para sahabat”[15].
Hadis dari Mu’adz Bin Jabal ra berkenaan dengan pengutusannya ke Yaman sangat jelas bagaimana ia berijtihad dengan ra’yu-nya. Dalam dialognya dengan Rasulullah saw yang ditulis oleh ad-Darimi dalam Sunannya menyebutkan: “Rasulullah bertanya kepada Mu’adz, Bila ada masalah yang menuntutmu menyelesaikannya bagaimana engkau akan menyelesaikannya?” “Aku akan menyelesaikannya dengan berpegangan pada Kitab Allah”, jawabnya. Rasulullah saw kembali bertanya: “Seandainya masalah yang engkau selesaikan tidak terdapat dalam Kitab Allah apa yang kau perbuat?” “Aku akan berpegangan dengan sunnah Rasulullah”, kembali Mu’adz menjawab. “Bila masalahnya tidak kau temukan dalam Kitab Allah dan sunnah RasulNya?”, tanya Nabi. Mu’adz menjawab: “Ajtahidu bira’yi” (aku akan berijtihad dengan pikiranku sendiri)…[16].
Syahid Shadr dengan lugas menangkap kenyataan ini dan menjelaskan: “… Madrasah fiqih Ahli Sunah memiliki kaidah berdasarkan ijtihad sebagai berikut: “Seorang fakih (ahli fiqih) bila hendak menyimpulkan sebuah hukum syar’i dan kemudian ia tidak mendapatkannya pada Al-Quran atau sunnah Nabi ia akan mengambil sikap ijtihad sebagai ganti dari teks-teks agama tersebut”.
Ijtihad di sini berarti pemikiran pribadi. Seorang fakih yang tidak menemukan teks-teks agama beralih pada pemikiran pribadi yang menuntunnya membuat hukum syar’i. Ijtihad seperti ini disebut Ijtihad Ra’yu.
Ijtihad dengan makna seperti ini menjadi salah satu argumentasi seorang fakih bahkan salah satu dari sumber hukum syar’i. Sebagaimana seorang fakih berpegangan pada kitab atau sunah dan berargumentasi dengan keduanya ia berpegangan dengan pendapat dan pikiran pribadinya ketika tidak menemukan dalil dari keduanya’[17].
Analisa ijtihad makna khusus
Di antara para sahabat Nabi yang berada dalam baris terdepan menggunakan kata ijtihad dengan makna khusus ini adalah khalifah kedua Umar bin Khattab ra. Sementara di kalangan tabi’in Rabi’ah bin Abdur Rahman dan Abu Hanifah dari kalangan tabi’ tabi’in. Bahkan Abu Hanifah dengan tegas menjadikan ra’yu sebagai ciri khas mazhabnya[18].
Dalam sejarah perkembangan kata ijtihad makna khusus ada tiga bentuk penafsiran. Pertama, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Ijtihad menjadi sumber hukum syar’i setelah al-Quran dan Sunah[19]. Kedua, Ijtihad makna khusus berada setara dengan al-Quran dan Sunah[20]. Ketiga, Ijtihad terkadang lebih didahulukan dari al-Quran dan Sunah[21].
Konsep ijtihad makna khusus yang diamalkan oleh Ahli Sunah dan lebih khususnya para sahabat merupakan sebuah keharusan sejarah. Sunah dalam konsep Ahli Sunah terbatas pada Nabi Muhammad saw. Hal ini membuat mereka harus segera mencari sumber lain selain dua sumber asli. Hal ini berbeda dengan Syiah yang meyakini konsep Imamah menganggap sunah berlanjut hingga 12 Imam. Berdasarkan kenyataan bahwa sunah hanya terbatas pada Nabi, membuat Ahli Sunah harus mengambil sikap ini. Hal ini kemudian ditambah dengan perluasan wilayah islam menambah kerumitan tersendiri bagaimana islam, dengan berpegangan hanya dengan Al-Quran dan Sunah, harus menyelesaikan masalah-masalah yang baru muncul. Dan satu faktor lain yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana menyimpulkan sebuah hukum dari dua sumber asli untuk menyelesaikan problem yang ada. Dengan kata lain, pada masa itu ilmu ushul belum ada. Metode penyimpulan hukum dari dua sumber asli belum terpikirkan oleh para sahabat.
Sumber hukum yang terbatas[22] dan konsep yang belum ada ditambah perluasan wilayah dan permasalahannya adalah faktor asli yang membuat para sahabat mengambil sikap ijtihad.
Hadis Mu’adz bin Jabal yang berisikan dialognya dengan Nabi ketika hendak diutus ke Yaman merupakan salah satu dalil kunci pemaknaan ini. Jawaban terakhirnya berkenaan dengan ijtihad ra’yunya mendapat pujian dari Nabi. Pujian inilah yang memberikan kekuatan hadis ini sebagai dasar bagi kata ijtihad. Untuk itu perlu sedikit kajian berkenaan dengan sanad hadis ini.
Dalam buku ‘Aunul Ma’bud disebutkan:
“Hadis ini oleh Al-Juzqani dikelompokkan dalam hadis maudhu’ (hadis yang dibuat-buat). Al-Juzqani berkata: “Hadis ini batil karena diriwayatkan oleh sekelompok perawi dari Syu’bah. Sementara hadis ini dinukil dalam perari-perawi baik besar maupun kecil. Aku bertanya kepada setiap muhaddis yang meriwayatkan hadis ini namun tidak kutemui jalur lain selain yang diriwayatkan oleh Syu’bah”.
Al-Harits bin Amr bin Akhil Mughirah bin Syu’bah seorang pribadi yang majhul, tidak diketahui latar belakangnya. Para sahabat Mu’adz yang ahli Hims tidak mengenalnya. Sanad yang seperti ini tidak dapat dijadikan pegangan dalam asli syareat. Bila dikatakan: “Mayoritas ahli fiqih meriwayatkan dan berpegangan dengan hadis Mu’adz”. Jawabannya adalah jalur hadis ini demikian adanya. Khalaf dalam hal ini telah mengikuti Salaf. Seandainya mereka menunjukkan jalur lain bagi hadis ini yang dapat diterima oleh ahli hadis, niscaya pandangan kami akan berubah mengikutinya. Namun, sayangnya, hal itu tidak mungkin terjadi[23].”
Ibnu Hazm Al-Andalusi pada beberapa tempat menyebutkan hadis ini sambil menegaskan batilnya hadis Mu’adz. Ibnu Hazm berkata:
“Hadis ini tak dapat dijadikan dalil. Tidak ditemukan seorang pun yang meriwayatkannya selain dari jalur ini. Tidak dapat dijadikannya hadis ini sebagai dalil lebih kembali kepada sekelompok orang yang meriwayatkan hadis ini. Mereka kelompok yang tidak dikenal dan tidak pernah disebut. Setiap perawi yang tidak dikenal riwayatnya tidak dapat dijadikan sebuah dalil. Dalam hadis tersebut ada seorang perawi yang bernama Al-Harits bin Amr. Seorang perawi yang tidak dikenal siapa dia (majhul). Hadis Mua’dz tidak pernah diriwayatkan selain dari jalur Al-Harits bin Amr[24].”
Di sebagian tempat Ibnu Hazm menukil dari Bukhari bahwa ia berkata: “Al-Harits tidak pernah dikenal kecuali dari jalur hadis Mu’adz dan ini tidak sahih’”[25].
Komentar-komentar ulama di atas membuat sulit untuk meyakini kebenaran hadis Mu’adz sebagai pembenaran makna ijtihad yang diinginkan oleh Ahli Sunah. Namun pun demikian, tidak dapat disandarkan makna ijtihad lewat hadis Mu’adz tidak membuat makna yang diinginkan tidak lagi dipakai. Ijtihad makna khusus adalah sudah merupakan fenomena yang diterima luas di kalangan Ahli Sunah dengan atau tanpa hadis Mu’adz. Yang dapat dibuktikan adalah makna yang diinginkan tidak lagi dapat disandarkan dengan hadis Mu’adz.
Kembali pada masalah ijtihad dengan makna khusus (ra’yu). Dalam perkembangannya, pada masa hidupnya para Imam empat mazhab belum menemukan formula baku. Hal itu dengan melihat cara mereka mengartikan kata ijtihad itu sendiri. Ditemukan adanya perbedaan mengenai apa yang dimaksud dengan ijtihad. Imam Syafi’i dengan tegas menyebutkan bahwa ijtihad adalah qiyas itu sendiri. Sementara yang lainnya menyebutkan istihsan atau mashalih mursalah. Jelas, bahwa qiyas bukan ijtihad begitu juga istihsan dan mashalih mursalah. Namun ketiganya adalah metode yang dipakai dalam berijtihad untuk menyimpulkan sebuah hukum.
Perbedaan yang ada dalam mengartikan kata ijtihad membuka sebuah peluang untuk menafsirkan kata ijtihad pada generasi awal islam (sahabat). Ijtihad yang dipakai generasi awal tidak jelas apa maksudnya dan terlepas dari pemaknaan positif dan tidak ada kaitannya dengan mazhab. Oleh karenanya, metode yang dipakai bukanlah qiyas yang dibangun oleh para Imam Mazhab. Ijtihad yang dipakai oleh para sahabat adalah bentuk qiyas yang masih sederhana dengan memakai tolok ukur maslahat. Maslahat pun tidak mendapat bingkai yang jelas. Bisa jadi maslahat kaum muslimin, Arab, kabilah atau pribadi.
Seiring dengan berlalunya waktu, kata ijtihad mulai mendapat batasan-batasan tertentu hingga akhirnya mengambil bentuknya yang baku. Itulah mengapa untuk membakukan makna ijtihad Syafi’i menyebutnya qiyas. Sementara yang lain istihsan atau mashalih mursalah[26].
Setelah jelas bahwa prinsip ijtihad yang dikembangkan oleh para sahabat yang kemudian disempurnakan oleh para imam mazhab muncul karena sebuah keharusan sejarah. Sumber hukum yang terbatas, belum adanya konsep dan permasalahan yang muncul akibat perluasan wilayah adalah alasan mengapa harus ijtihad makna khusus. Ijtihad yang dikembangkan juga masih dalam bentuk yang sederhana yang kemudian mengalami penyempurnaan pada masa imam mazhab. Di sisi lain, hadis Mu’adz tidak dapat menjustifikasi makna yang diinginkan Ahli Sunah bagi ijtihad. Perlu kiranya mendudukan prinsip yang dikembangkan ini dalam sebuah perspektif yang lebih luas dan dampaknya bagi islam.
Untuk memulai kajian yang lebih luas, berkaitan dengan ijtihad makna khusus, ada baiknya kalau kembali melihat pikiran inti dari ijtihad makna khusus ini. Pikiran tersebut, dengan menukil ucapan Syahid Shadr, sebagai berikut:
“Seorang fakih (ahli fiqih) bila hendak menyimpulkan sebuah hukum syar’i dan kemudian ia tidak mendapatkannya pada Al-Quran atau Sunnah Nabi ia akan mengambil sikap ijtihad sebagai ganti dari teks-teks agama tersebut.
Ijtihad di sini berarti pemikiran pribadi. Seorang fakih yang tidak menemukan teks-teks agama beralih pada pemikiran pribadi yang menuntunnya membuat hukum syar’i. Ijtihad seperti ini disebut Ijtihad Ra’yu.
Ijtihad dengan makna seperti ini menjadi salah satu argumentasi seorang fakih bahkan salah satu dari sumber hukum syar’i. Sebagaimana seorang fakih berpegangan pada kitab atau sunah dan berargumentasi dengan keduanya ia berpegangan dengan pendapat dan pikiran pribadinya ketika tidak menemukan dalil dari keduanya[27].”
Seandainya dicoba membandingkan proses munculnya sebuah hukum yang dihasilkan oleh seorang fakih lewat ijtihad didapatkan kesamaan dengan proses munculnya sebuah hukum yang tertera dalam al-Quran atau hadis Nabi. Ilustrasinya demikian, pada al-Quran, Allah adalah sang pembuat hukum. Al-Quran adalah sumbernya sementara teks yang tertera adalah dalil yang menunjukkan adanya sebuah hukum. Pada hadis, Nabi, dengan ijin Allah[28], adalah pembuat hukum. Hadis adalah sumbernya sementara teks hadis adalah dalil yang menunjukkan adanya sebuah hukum. Pada proses ijtihad, Mujtahid[29] adalah pembuat hukum (setelah mencari dan tidak menemukan pada dua sumber asli). Fatwa mujtahid adalah sumber hukum sementara teks fatwa adalah dalil yang menunjukkan adanya sebuah hukum.
Dengan berpegangan pada ilustrasi di atas, mendudukkan seorang mujtahid setara dengan Nabi, sebagai pembuat hukum ilahi, memerlukan argumentasi yang lebih kuat dari sekedar dalil yang menyebutkan bahwa seorang mujtahid bila benar mendapat dua pahala sedangkan bila salah mendapat satu pahala. Dalil yang diperlukan harus qat’i, jelas, kuat dan disepakati kaum muslimin. Mengingat Nabi sendiri harus mendapat mandat untuk dapat melakukan tugas berat tersebut agar hukum yang keluar darinya tidak dipandang sebagai produk pribadi yang lebih sering dipengaruhi faktor-faktor emosi dan lingkungan[30]. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, bila ingin produk hukum yang dibuat akan diberi stempel ilahi. Nabi sendiri selaku pribadi yang mempunyai hak membuat undang-undang (hukum ilahi), oleh kaum muslimin, tidak pernah diposisikan sama dengan Allah.
Lebih dari itu, Mendudukkan seorang mujtahid setara dengan Allah sebagai pembuat hukum ilahi adalah sangat sulit diterima. Ayat Al-Quran menyebutkan: “Inil Hukmu Illaa Lillaah”. Hukum hanyalah milik Allah. Tanpa mengajukan argumentasi kuat lewat Al-Quran posisi mujtahid sebagai pembuat hukum setara dengan Allah hanya sebuah dakwaan belaka. Dan, bagaimana mungkin teori yang sulit dipertanggungjawabkan seperti ini menjadi prinsip mazhab Ahli Sunah. Sebuah prinsip yang tidak hanya sulit di kalangan ahli fiqih dan ushul namun juga pada tataran teologi. Allah adalah Esa sampai pada tataran pembuatan hukum (tauhid fi tasyri’).
Pada sisi yang lain, terlihat bahwa ahlus sunah dengan penjelasan di atas mengalami kerancuan dalam usaha membedakan antara khitab (teks ) dan hukum. Hukum Allah berkaitan dengan ilmu-Nya. Sementara ayat-ayat yang berada dalam Al-Quran adalah teks-teks yang menunjukkan adanya hukum Allah. Hukum Allah tidak selamanya tertera dalam al-Quran. Hukum Allah terkadang mengambil bentuk sebagai teks-teks Al-Quran, terkadang berbentuk hadis qudsi, hadis-hadis yang diucapkan Nabi perbuatan atau taqrirnya. Hukum Allah terkadang tersembunyi pada sebuah teks umum yang kemudian dipersempit oleh hadis atau akal atau yang lainnya[31].
Dengan penjelasan di atas, Hukum Allah terkadang diketahui oleh mujtahid sejauh eksplorasinya terhadap sumber-sumber hukum syar’i, terkadang ia tidak mengetahuinya. Tidak seorang pun yang dapat mendakwa bahwa ia mengetahui semua hukum Allah tanpa terkecuali. Hukum Allah terkait erat dengan ilmu dan iradah-Nya. Oleh karenanya, ketika disebutkan seorang mujtahid tidak menemukan hukum Allah sebenarnya ia tidak menemukan teks yang langsung berkaitan dengan masalah yang dihadapinya. Tidak menemukan teks tidak langsung berarti tidak menemukan hukum. Sebuah perbedaan yang sangat besar.
Sekarang masuk pada permasalahan yang lebih besar dan lebih penting dan itu berkaitan dengan hukum Allah. Hukum Allah sebagaimana yang diyakini kaum muslimin adalah universal. Hukum Allah kekal dan mampu menjawab semua tantangan zaman. Keduanya dakwaan yang disepakati oleh kaum muslimin. Hukum Allah kekal sesuai dengan janji Allah akan kekekalan al-Quran. Sementara hukum islam mampu menjawab tantangan zaman sampai saat masih memiliki ujian bahkan semakin berat. Argumentasi terkait dengan dakwaan ini kembali kepada Zat Allah sendiri. Allah swt adalah Zat Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Sesuai dengan sifat yang dimilikiNya hukum yang dipersiapkan tentunya adalah hukum yang sempurna sesuai dengan kesempurnanNya. Dengan dasar ini, tidak ada satu fenomena apapun yang terjadi di dunia ini tanpa hukum Allah[32]. Sekali lagi, bedakan antara teks dan hukum.
Ahli Sunah dengan mengatakan bahwa ketika seorang mujtahid tidak menemukan hukum maka ia berijtihad. Tanpa disadari ada sebuah bentuk pengakuan bahwa hukum Allah tidak sempurna. Hukum Allah tidak mencakup masalah-masalah yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sederhana, namun memiliki konsekuensi yang sangat berat. Meyakini bahwa hukum Allah tidak sempurna dengan sendirinya kebijakan dan pengetahuan Allah dipertanyakan. Ketidaksempurnaan hukum Allah, oleh Ahli Sunah, bagaimanapun juga harus diisi untuk tetap memberikan kesan kemampuan syariat islam menjawab tantangan zaman. Sayangnya, kemampuan tersebut tidak diseimbangkan dengan menempa sistem yang lebih baik dalam menyimpulkan hukum syar’i. Lebih dari itu, Ahli Sunah mencoba memberikan porsi yang lebih kepada para mujtahid berkreasi memproduksi hukum syar’i.
Keyakinan akan ketidaksempurnaan hukum Allah harus dibayar mahal oleh Ahli Sunah. Mereka terpaksa memperbolehkan mujtahid ikut campur tangan mengisi “Ruang Kosong” yang ditinggalkan oleh Allah. Kesempurnaan hukum Allah akan menjadi bermakna dengan tambahan hukum yang diproduksi oleh sang mujtahid, siapa saja.
Para Imam Syiah dengan lantang menyampaikan ketidaksetujuan mereka berkenaan dengan pandangan yang seperti ini:
1. Dari Imam Shadiq as diriwayatkan: “Sesungguhnya Allah swt telah menurunkan di dalam al-Quran penjelas segala sesuatu dan Allah tidak meninggalkan sesuatu pun yang dibutuhkan oleh seorang hamba sehingga ia tak dapat berkata: “Alangkah baiknya bila hal ini diturunkan Allah dalam al-Quran”. Allah telah menurunkan semua yang dibutuhkan hambanya”[33].
2. Riwayat dari Imam Shadiq as: ”Tidak ada sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Quran atau sunah”[34].
3. Abu Bashir bertanya kepada Imam Shadiq as: “Kami menemukan beberapa masalah yang hukumnya tidak kami dapatkan baik di dalam al-Quran maupun sunah Nabi. Bolehkah kami berpendapat sesuai dengan pandangan pribadi kami? Imam menjawab: “Tidak. Ketahuilah, pendapat pribadimu sesuai dengan kebenaran engkau tidak akan mendapat pahala karenanya. Dan, agar pendapat pribadimu tidak benar, engkau telah berdusta atas nama Allah”[35].
Ketidaksetujuan ini sebenarnya tidak hanya dari mazhab Syiah Imamiyah, namun mendapat reaksi yang cukup keras dari tubuh Ahli Sunah sendiri. Hal itu ditandai dengan munculnya mazhab Zhohiri, pada pertengahan abad ke tiga hijriah, yang dipelopori oleh Daud bin Ali bin Khalaf Al Ishbahani. Ia menyerukan untuk beramal sesuai dengan apa yang tertera dalam al-Quran dan Sunah Nabi tidak lebih. Ini jelas sangat bertentangan dengan pendapat di atas yang lebih menekankan peran pendapat pribadi manusia setara dengan hukum Allah.
Ulama Syiah dan sebagian sahabat para Imam as menulis buku yang isinya menolak ijtihad dengan makna khusus. Berikut ini sebagian nama dan tulisannya:
1. Abdullah bin Abdur Rahman az Zubairi, Al-Istifadah fi At Thu’un ‘ala Al-Awail wa Ar Raddu ‘ala ashabil ijtihad wa Al-Qiyas (… dan menolak pengikut ijtihad dan qiyas).
2. Hilal bin Ibrahim bin Abi Al-Fath Al-Madani, Ar Raddu ‘ala Man Radda Atsar Ar Rasul wa ‘Itamada ‘ala Nataiji Al-‘Uqul (Menolak siapa yang menolak hadis-hadis Rasul dan berpegangan dengan kesimpulan-kesimpulan akal).
3. Ismail bin Ali bin Ishaq bin Abi Sahl An-Naubakhti, Ar Raddu ‘ala ‘Isa bin Aban Fi Al-Ijtihad (Menolak Isa bin Aban dalam masalah ijtihad).
4. Syaikh Shaduq ra dalam bukunya Al Muqni’ah menuliskan: “Sesungguhnya Musa as, dengan segala kesempurnaan akal, keutamaan dan kedekatannya di sisi Allah, tidak mengetahui dengan argumentasi yang dimilikinya apa arti perilaku Khidir as sehingga ia rancu menghukuminya. Bila tidak diperbolehkan seorang Nabi dan Rasul Allah untuk melakukan qiyas maka sudah barang tentu orang-orang selainnya lebih patut untuk tidak melakukan itu …”.
5. Syaikh Mufid, An-Naqdhu ‘ala Ibnil Junaid fi Ijtihadi Ar Ra’yu (mengkritik Ibnul Junaid dalam masalah ijtihad bir ra’yi).
6. Sayyid Murtadha dalam buku Adz Dzari’ah menulis: “Ijtihad adalah batil hukumnya. Imamiyah tidak memperbolehkan pengikutnya untuk beramal dengan zhan (persangkaan), ra’yu dan ijtihad”.
Melangkah lebih jauh mengamati ijtihad makna khusus akan ditemukan sebuah pembahasan yang lebih menarik. Dan itu berkaitan dengan usaha penjustifikasian perbedaan pendapat para mujtahid. Sebuah pertanyaan sederhana. Namun jawaban pertanyaan ini telah melahirkan dua peta pemikiran besar dalam ijtihad. Pertanyaan tersebut berbunyi, bila terjadi perbedaan pendapat antara dua atau lebih mujtahid manakah yang benar?
Jawaban pertanyaan ini memunculkan istilah tashwib dan takhtiah. Ahli Sunah menjadikan tashwib sebagai landasan pemikiran mereka sementara Syiah dengan takhtiah.
Syiah dengan mengusung takhti’ah berpendapat bahwa Allah memiliki hukum di semua bidang kehidupan manusia. Tidak ada satu kondisi dari kehidupan manusia yang kosong dari hukum Allah[36]. Hanya saja terkadang manusia mengetahuinya dan terkadang tidak. Ketidaktahuan manusia akan hukum Allah tidak sama dengan ketiadaan hukum Allah. Peran akal di sini hanyalah sebagai penyingkap hukum Allah, bukan penentu sebuah hukum. Akal manusia hanya menuntun dan menyingkap hukum Allah. Oleh karenanya, seorang mujtahid dapat salah dan juga dapat benar. Takhti’ah artinya seorang mujtahid dalam usahanya menyingkap hukum Allah boleh jadi benar dan boleh jadi salah. Dan di sini, kesalahannya dimaafkan.
Sementara Ahli Sunah, sesuai dengan keterangan sebelumnya yang memaknai ijtihad dengan makna khusus, memilih tashwib sebagai keharusan logis. Dengan pemaknaan khusus ini, sadar atau tidak, Ahli Sunah meyakini bahwa Allah tidak memiliki hukum di semua bidang kehidupan manusia. Ada kondisi-kondisi di mana Allah tidak memberikan hukum. Oleh karenanya, ketika tidak ditemukan hukum tersebut seorang mujtahid akan menyandarkan pendapat pribadinya sebagai hukum sejajar dengan hukum Allah. Dan, bila terjadi perbedaan pendapat dengan seorang mujtahid lainnya maka kedua-duanya benar. Kebenaran semua pendapat mujtahid yang berbeda pendapat dalam memproduksi hukum syar’i mendapat justifikasi penuh dengan kaidah tashwib. Tashwib adalah pembenaran. Hal itu tidak lain dikarenakan pendapat setiap mujtahid adalah hukum yang sejajar dengan hukum Allah.
Satu-satunya sumber yang membagi tashwib menjadi dua kelompok disebutkan oleh Syaikh Muhammad Ali Al-Kazhimi. Ia dalam bukunya membagi tashwib menjadi Tashwib Asy’ari dan Tashwib Mu’tazili[37]. Apa alasan menjadikan pembagiannya dengan memakai istilah Asy’ari dan Mu’tazili tidak dijelaskan. Hanya saja dapat dikatakan bahwa Tashwib Asy’ari adalah bentuk ekstrim dari tashwib, sementara Tashwib Mu’tazili menunjukkan bentuk moderatnya.
Al-Ghazali mendefinisikan tashwib yang diyakininya sebagai berikut:
“Tidak ada hukum tertentu bagi sebuah fenomena yang tidak ada teksnya. Hukum dicari lewat zhan (persangkaan). Lebih tepat, hukum mengikuti zhan. Hukum Allah bagi setiap mujtahid adalah zhan yang dimilikinya[38].”
Al-Ghazali dan sebagian ulama meyakini pandangan ini[39]. Tashwib yang diyakini ini disebut Tashwib Asy’ari.
Sebagian sumber-sumber menisbatkan tashwib Mu’tazili kepada As Syafi’i. Tashwib Mu’tazili berpendapat:
“Setiap fenomena yang tidak memiliki teks mempunyai hukum tertentu bila hendak dicari. Akan tetapi, seorang mujtahid tidak memiliki kewajiban untuk mencari dan sampai kepada hukum tersebut. Ia tetap dianggap benar sekalipun pada kenyataannya salah berkaitan dengan hukum tersebut”[40].
Pemikiran tashwib membuka sebuah medan baru bagi akal dalam proses ijtihad. Mengingat syareat atau hukum Allah memiliki kekurangan dan tidak sempurna, akal tidak lagi hanya berperan sebagai penyingkap hukum syar’i. Namun, dengan tashwib ia adalah pembuat hukum syar’i sejajar dengan Allah.
Yang lebih menarik adalah pandangan tashwib yang coba digagas oleh ulama Ahli Sunah ternyata tidak mendapat pengakuan dari Imam Empat.
Imam Abu Hanifah berkata: “Kami tahu bahwa ini adalah pendapat kami. Ini adalah yang paling mampu kami lakukan. Bila ada yang mampu membawakan pandangan yang lebih baik niscaya itulah yang benar. Tidak benar seorang yang tetap berpendirian dengan pendapat kami sekalipun ia mengetahui dari mana munculnya pendapat kami tersebut”[41].
Imam Malik berkata: “Saya adalah manusia juga yang dapat salah dan benar. Perhatikan dan telitilah pendapat ku. Bila ia sesuai dengan al-Quran dan Sunah maka ambillah pendapat ku. Sementara pendapat ku yang tidak sesuai dengan keduanya jangan diikuti”[42].
Imam Syafi’i berkata: “Jangan kalian mengikuti semua pendapatku. Perhatikan dan telitilah dalam pendapat ku karena ini adalah masalah agama”[43].
Hal ini juga yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal melarang taklid.
Imam Ali as dengan cepat dan tanggap melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang membahayakan agama. Dan itu tidak lain karena kesimpulan pemikiran ini berujung pada tidak sempurnanya agama yang pada gilirannya menganggap Allah sang pemilik agama sebagai Zat yang tidak lagi Maha Mengetahui.
Imam Ali as dalam Nahjul Balaghah pada khutbah yang ke delapan belas menyebutkan:
“Masyarakat membawa sebuah permasalahan yang berkenaan dengan sebuah hukum kepada seorang hakim[44]. Sang hakim menghukumi dengan pendapat pribadinya. Masalah yang sama di hadapkan kepada seorang hakim yang lain, ia menghukumi berbeda dengan hakim pertama. Kemudian para hakim dikumpulkan di hadapan pemimpin yang mengangkat mereka kemudian ia membenarkan semua pendapat yang ada. Sementara Tuhan mereka satu. Nabi mereka satu. Kitab mereka juga satu.
Apakah Allah swt memerintahkan mereka untuk berselisih paham kemudian ditaati ataukah Allah melarang mereka berselisih paham untuk kemudian dikhianati? Apakah Allah swt menurunkan agama yang tidak sempurna sehingga meminta pertolongan kepada mereka agar menyempurnakannya? Apakah mereka adalah sekutu Allah dalam penyempurnaan agama? Mereka yang berpendapat sementara Allah yang mengiakan dan memberikan stempel legalitas? Apakah Allah menurunkan agama yang sempurna kemudian Nabi saw tidak menyampaikannya dengan sempurna?
Bukankah Allah swt berfirman: “… Kami tidak meninggalkan sesuatupun kecuali menyebutkannya dalam al-Quran…”[45]. “… Dan di dalam al-Quran dijelaskan segala sesuatu …”[46]. Allah mengingatkan bahwa sebagian al-Quran membenarkan yang lainnya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Allah berfirman, “… Seandainya al-Quran tidak diturunkan oleh Allah niscaya mereka akan menemukan perselisihan yang banyak di dalamnya”[47].
Sesungguhnya al-Quran memiliki tampakan luar yang indah sementara batinnya sangat dalam. Keajaiban-keajaibannya tidak akan pernah sirna. Rahasia-rahasia yang dikandungnya tidak akan pernah ada habis-habisnya digali. Dan, kegelapan tak akan pernah dapat berubah terang tanpanya[48].”
2. Ijtihad makna umum
Mencermati pemaknaan ijtihad secara khusus dapat ditemukan bahwa ijtihad dilakukan ketika tidak ada nash (teks). Ijtihad dilakukan ketika tidak ditemukan teks ayat Al-Quran atau teks dari hadis Nabi. Dengan berlalunya waktu, ijtihad mengalami perkembangan yang cukup berarti. Qiyas yang sebelumnya diamalkan untuk memberikan hukum pada masalah yang tidak memiliki teks diperluas berkaitan dengan teks-teks. Qiyas tidak lagi terpenjara hanya terkait dengan masalah yang tidak memiliki teks saja. Bahkan lebih dari itu, usaha-usaha penyempurnaan ilmu usul fiqih semakin mendapat perhatian. Terutama berkaitan dengan masalah memahami teks.
Abu Al-Husein Al-Bashri dalam bukunya menuliskan: “Ketahuilah bahwa para fakih mengategorikan masalah-masalah ijtihad berkaitan juga dengan al-Quran seperti niat dalam berwudu dan tertib (satu persatu), demikian juga bahwa huruf Wau memiliki arti tertib dan terkumpul…”[49]. Lebih dari itu, Imam Gazali berpendapat bahwa cakupan ijtihad tidak keluar dari bingkai teks. Alasan beliau terkait erat dengan sumber-sumber dalil yang menurutnya ada empat, al-Quran, Sunah, Ijma’ dan dalil akal dan ishtishab yang keduanya menunjukkan tidak adanya pertanggungan jawab seorang mukallaf di hadapan Allah sebelum ada teks yang sampai padanya”[50].
Terlihat sebuah perbedaan yang sangat mendasar berkaitan dengan pandangan ulama sebelumnya yang membatasi ijtihad hanya pada masalah yang tidak memiliki teks, sementara ulama setelah mereka menjadikan teks sebagai kajian ijtihad. Pada awalnya ijtihad adalah al-intaj al-ma’rifi (hasil pemikiran) sementara sekarang berubah menjadi fahm an-nash (memahami teks).
Sebagian lainnya tidak hanya terhenti pada teks tetapi melebarkannya mencakup masalah-masalah akal. Sebagaimana dapat ditemukan pada definisi ijtihad yang ditulis oleh Syaikh Abu Muhammad as-Salimi (W. 1332 H). Ia mendefinisikan ijtihad sebagai: “Usaha keras seorang fakih untuk mendapatkan masalah lewat syariat (Al-Quran dan Sunah) atau akal. Sesungguhnya saya menyebutkan itu mencakup akal karena ijtihad juga berlaku padanya”[51]. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sebuah usaha untuk meluaskan sumber-sumber hukum syar’i yang oleh masyhur ulama Ahli sunah ada empat, al-Quran, Sunah, Ijma’ dan Qiyas. Dan sebagaimana diketahui qiyas adalah bagian dari hasil-hasil akal.
Berbeda dengan perkembangan makna ijtihad pada mazhab Ahli Sunah, Syiah tidak mengenal tahapan al-intaj al-ma’rifi. Bahkan dapat dikatakan bahwa ulama Syiah sebelum Muhaqqiq Al-Hilli (W. 676 H) tidak menerima ijtihad makna khusus. Tidak hanya menolak bahkan dalam tulisan-tulisan mereka ijtihad dengan makna seperti itu dianggap batil. Pendapat semacam ini dapat ditelusuri pada tulisan-tulisan ulama besar Syiah seperti, Syaikh Shaduq, Syarif Al-Murtadha, Syaikh Mufid dan Syaikh Thusi[52].
Syiah, sejak awal, memaknai ijtihad sebagai fahm an-nash, namun tidak berarti terhenti pada teks dengan pendekatan bahasa belaka melainkan telah berkembang lebih jauh dari itu. Hal itu dikarenakan, sejak awalnya, sumber-sumber ijtihad yang diakui oleh Syiah mencakup akal.
Definisi ijtihad, menurut Syiah, untuk pertama kalinya ditulis dan diterima oleh Muhaqqiq al-Hilli. Beliau dalam bukunya Ma’arij al-Ushul bab 9 berkaitan dengan hakikat ijtihad menulis:
“Ijtihad menurut fuqaha adalah usaha untuk mengeluarkan/menyimpulkan hukum-hukum syar’i. Dengan ini, mengeluarkan hukum syar’i dari dalil-dalil syar’i merupakan ijtihad. Hal ini dikarenakan mengeluarkan hukum-hukum syar’i berdasarkan sebuah proses pemikiran dan tidak semata-mata dari zuhur teks-teks. Proses berpikir dapat berupa qiyas atau selainnya. Berdasarkan ini qiyas juga merupakan bagian dari ijtihad.
Bila dipertanyakan bahwa apakah itu berarti Syiah juga berijtihad? Jawabannya adalah ‘iya’. Permasalahannya adalah dalam ijtihad ada bagian yang disebut qiyas dan ini terkadang membingungkan. Kebingungan itu lebih pada hubungan qiyas dan ijtihad. Bila menerima ijtihad tanpa qiyas juga masih dapat disebut sebagai ijtihad maka sekali lagi Syiah juga berijtihad dengan tanpa qiyas”[54].
Tulisan Muhaqqiq al-Hilli dengan gamblang menerangkan bagaimana di kalangan Syiah kata ijtihad pernah memiliki nilai negatif. Ia juga mengakui bahwa untuk sebagian orang menerima kata ijtihad adalah berat. Terlebih lagi menyandarkan predikat mujtahid kepada seorang dari ulama Syiah. Namun semua itu ditepis olehnya dan bahkan ia berani untuk menyebut dirinya sebagai mujtahid. Tentunya dengan menepis terlebih dahulu pengertian negatif yang dimilikinya sebelumnya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan Muhaqqiq al-Hilli dipengaruhi oleh perubahan makna yang terjadi di kalangan ulama Ahli Sunah. Setidak-tidaknya makna umum yang diberikan oleh al-Ghazali (W. 505 H) yang wafat sebelum Muhaqqiq al-Hilli. Definisi yang diusung oleh al-Ghazali dan sebagian ulama yang lain telah menekan dan memperkecil penggunaan ra’yu dan qiyas untuk memproses sebuah hukum syar’i. Dan untuk itu medan yang lebih besar diberikan kepada usaha keras secara ilmiah untuk menyimpulkan sebuah hukum. Syahid Muthahhari menangkap perubahan ini dan menyebutkan bahwa setelah terjadi perubahan yang sangat mendasar, kata ijtihad masuk dalam khazanah fiqih Syiah[55].
Tulisan Muhaqqiq al-Hilli tidak hanya sebagai peletak dasar pemakaian kata ijtihad dalam Syiah namun, lebih dari itu, ide-ide pikiran beliau sebenarnya juga menjadi titik tolak bentuk dari “memahami teks”. Ulama sebelumnya memahami korespondensi antara teks dan usaha memahaminya adalah hubungan identik. Artinya, proses penyimpulan hukum (baca: ijtihad) harus sampai pada sebuah ilmu dan keyakinan. Sementara itu, semenjak munculnya Muhaqqiq al-Hilli hingga sekarang hubungan antara teks dan usaha memahaminya adalah tidak identik[56]. Usaha yang dilakukan dapat saja salah dan tidak menghasilkan sebuah ilmu dan keyakinan[57].
Muhaqqiq al-Hilli dengan tulisannya membawa terobosan besar dalam fiqih Syiah sekaligus langkah ke depan terbentuknya sebuah dialog dalam masalah penyimpulan hukum syariat dengan mazhab Ahli Sunah. Sayangnya, ini tidak ditangkap dengan serius oleh kedua belah pihak sepeninggal Muhaqqiq al-Hilli.
Beberapa definisi ijtihad makna umum
Berkenaan dengan definisi ijtihad makna umum terjadi perbedaan di antara ulama baik Ahli Sunah maupun Syiah. Setiap ulama memiliki penafsiran tersendiri. Namun perbedaan dalam pendefinisian ini tidak ditangkap sebagai perbedaan pada esensi ijtihad makna umum itu sendiri. Esensi ijtihad diterima oleh seluruh Ulama. Perbedaan yang ada lebih muncul pada tambahan definisi yang biasanya muncul dari hal lain bukan ijtihad itu sendiri. Sebagaimana perkembangan yang terjadi pada ruang lingkup ijtihad. Ada yang menambahkan kata zhan (persangkaan) atau ilmu (keyakinan), di samping ada juga yang menambahkan kata fakih pada definisi bahkan ada yang menambahkan kata malakah (karakter tetap).
Definisi yang diusulkan oleh ulama Islam berkaitan dengan ijtihad bukanlah hakikat yang sebenarnya. Definisi yang diajukan lebih banyak sebagai komentar dan penjelas terhadap kata ijtihad itu sendiri.
1. Definisi dengan tambahan zhan (persangkaan)
Saifuddin al-Amidi as-Syafi’i (W. 631 H) berkata:
“Ijtihad adalah usaha serius untuk sampai pada zhan tentang hukum syar’i sehingga seseorang akan merasakan bahwa sulit dibayangkan kemampuannya lebih dari itu”[58].
Ibnu Subki berpendapat:
“Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk menghasilkan zhan terhadap hukum syar’i”[59].
Allamah Al-Hilli mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:
“Ijtihad adalah mengusahakan semua kemampuan untuk memberikan pendapat pada masalah zhan tentang hukum syar’i. Usaha yang dilakukan adalah puncaknya sehingga kemungkinan lebih dari itu adalah sangat sulit dibayangkan”[60].
Kritik definisi
Memberikan tambahan definisi ijtihad dengan kata zhan tidak tepat. Hal itu karena tambahan ini menafikan kemungkinan mendapatkan ilmu dan keyakinan dengan berijtihad. Bila dibayangkan bahwa selamanya yang dihasilkan dengan berijtihad adalah zhan maka itu berarti kemungkinan menghasilkan ilmu adalah tidak mungkin sementara hal ini tidak pernah diterima. Penambahan kata zhan mungkin dapat diterima dengan mengandaikan bahwa sebelumnya dengan ijtihad, ilmu dan keyakinan yang dihasilkan. Dan penambahan zhan ingin menambahkan bahwa tidak selamanya ijtihad menghasilkan ilmu dan keyakinan namun lebih sering kesimpulan yang dihasilkan adalah zhan. Bila kemungkinan seperti ini yang dimaksud tentu dapat diterima.
Penafsiran kedua ini juga masih lemah mengingat hasil dari ijtihad juga tidak selamanya ilmu dan zhan namun bisa tidak keduanya. Artinya, kesimpulan yang dihasilkan dari ijtihad boleh jadi tidak pada derajat zan apalagi ilmu, derajatnya kurang dari zhan. Bila ingin diperinci lebih detil maka hasil atau dalil yang diproses dari ijtihad memiliki sekurang-kurangnya tiga kondisi. Terkadang menghasilkan ilmu, zhan atau di bawah zhan. Kemungkinan ketiga itu dapat ditemukan pada hasil ijtihad yang lemah. Tentunya hasil sebuah metodologi ijtihad yang lemah pula.
Di sisi lain, dalam Islam beramal dengan zhan adalah sesuatu yang tidak terpuji[61]. Tentunya tidak semua zhan dalam Islam tidak diterima. Hadis Ahad atau khabar wahid adalah salah satu contohnya. Hadis yang diriwayatkan oleh sedikit perawi/satu perawi dan paling banyak diriwayatkan oleh tiga orang[62], bila yang meriwayatkan adalah tepercaya (tsiqah/adil) maka beramal dengan hadis tersebut adalah diperbolehkan. Dengan ini, ulama membagi beramal dengan zhan menjadi dua bagian. Zhan yang mu’tabar (yang diterima) dan zhan yang tidak mu’tabar. Zhan disebut mu’tabar karena ditopang oleh dalil-dalil, baik itu dari al-Quran dan atau perilaku orang-orang berakal (siroh ‘uqola) atau kearifan umum. Sementara zhan yang tidak mu’tabar adalah kebalikannya. Ia tidak ditopang oleh dalil-dalil. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak tepercaya (tsiqoh/adil).
2. Definisi dengan tambahan ilmu (keyakinan)
Al-Ghazali (W. 505 H) menulis:
“Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Kata ijtihad dipergunakan untuk sesuatu yang sulit. Kata ijtihad dipergunakan untuk orang yang berusaha sekuat tenaga untuk memindahkan batu yang berukuran besar bukan untuk memindahkan kerikil. Kata ijtihad kemudian dalam terminologi ulama fiqih dikhususkan pada usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu (keyakinan) lewat hukum syar’i. Ijtihad yang sempurna adalah usaha sungguh-sungguh unuk mendapatkan ilmu sehingga ia merasa ini adalah puncak usahanya”.
Khudhri Bik dalam buku Ushul Fiqihnya menulis:
“Seorang fakih berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu (keyakinan) berkaitan dengan hukum syar’i”.
Kritik definisi
Definisi yang menambahkan kata ilmu dalam pendefinisiannya memiliki kelemahan yang sama dengan definisi yang memiliki tambahan kata zhan. Dan kritikan yang diajukan di atas tidak jauh berbeda dengan definisi ini. Namun kritikan tersebut dapat dimentahkan dengan satu catatan bahwa kata ilmu yang dipakai dimaknai secara umum. Kata ilmu yang dimaksud mencakup ilmu wujdani dan ilmu ta’abbudi. Ilmu wujdani adalah ilmu yang identik dengan keyakinan dalam logika. Sementara ilmu ta’abbudi sebenarnya adalah zhan (persangkaan) yang kemudian oleh syariat diberi justifikasi untuk dapat dipergunakan sebagai dalil. Ilmu ta’abbudi seperti beramal dengan Hadis Ahad yang diriwayatkan oleh seorang perawi tepercaya yang telah diberi legitimasi oleh syariat.
3. Definisi dengan tambahan fakih
Syahid Tsani dalam bukunya mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:
“Usaha sungguh-sungguh seorang fakih untuk mendapatkan zhan (persangkaan) tentang hukum syar’i”.
Penulis buku Al-Fushul fi Al-Ushul menyebutkan:
“Ijtihad adalah puncak usaha dari seorang fakih untuk mendapatkan zhan tentang hukum syar’i”.
Kritik definisi
Dapat dikatakan bahwa definisi yang mendapatkan tambahan kata fakih adalah definisi yang paling banyak menghadapi keberatan. Hal itu tidak lepas dari proses melakukan ijtihad hanya terbatas pada seorang mujtahid dan seorang mujtahid adalah kata lain untuk fakih. Oleh karenanya menjadi sia-sia memasukkan kata fakih dalam definisi.
4. Definisi dengan tambahan kata malakah (kecakapan penalaran)
Sebagian ulama ketika mendefinisikan ijtihad menambahkan kata malakah. Sebagai contoh Syaikh Baha’i dalam bukunya mendefinisikannya sebagai berikut:
“Ijtihad adalah sebuah malakah dan instrumen yang membantu manusia memiliki kemampuan untuk menyimpulkan hukum syar’i”.
Sementara Mujtaba Tehrani pada catatan kaki buku Rasail milik Syaikh Anshari mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:
“Definisi yang paling dekat untuk memerikan kata ijtihad adalah definisi ma’ruf yang berbunyi ijtihad adalah malakah atau sebuah kemampuan yang dengan itu seseorang mampu untuk menyimpulkan sebuah hukum syar’i”.
Kritik definisi
Definisi ini walaupun dapat menepis kritikan-kritikan pada definisi-definisi sebelumnya namun pada saat yang sama mendapatkan keberatan yang tidak mudah untuk dijawab. Keberatan pertama berkenaan dengan definisi yang menambahkan kata malakah. Hakikat ijtihad bukanlah malakah. Mengapa demikian? Karena bila ijtihad memiliki arti malakah maka penambahan itu memiliki unsur penjelas sementara yang terjadi tidak demikian. Penambahan kata malakah seperti penambahannya terhadap sifat adil.
Keberatan kedua adalah malakah dihasilkan dengan melatih ilmu-ilmu pengantar agar seorang dapat menjadi mujtahid. Seseorang yang telah menguasai pengantar ilmu-ilmu untuk dapat berijtihad adalah seorang mujtahid sekalipun dia belum pernah melakukan ijtihad, belum pernah menyimpulkan sebuah hukum. Sekali lagi, malakah berijtihad bukan ijtihad itu sendiri tapi muncul dari kecakapan penalaran yang didapatkan dengan melatih pengantar ilmu-ilmu ijtihad.
Keberatan ketiga terkait erat dengan penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan ijtihad dalam riwayat-riwayat. Dalam hadis-hadis disebutkan beberapa kata seperti ‘arafa ahkamana (yang mengetahui hukum-hukum kami), nazhara fi halalina wa haramina (yang memiliki kecakapan dalam memahami halal dan haram kami), rawa’ haditsana (yang meriwayatkan hadis kami). Bila kita mengartikan ijtihad dengan malakah (masih pada tahapan potensi) maka mereka yang secara aktual (bil fi’l) mampu menyimpulkan hukum tidak termasuk dalam hadis di atas. Sementara tidak satu pun ulama yang meyakini hal itu. Karena hadis itu sifatnya umum mencakup keduanya tidak dikhususkan hanya yang memiliki malakah.
Ada beberapa definisi yang tidak menggunakan tambahan-tambahan di atas namun pun demikian masih rentan terhadap kritikan. Imam Khomeini dalam buku Ar-Rasail mendefinisikan ijtihad sebagai proses pengembalian furu’ kepada asal (mengembalikan cabang masalah pada pokoknya). Bahkan oleh beliau ditambahkan bahwa pada masa kini ijtihad tidak lebih dari proses pengembalian furu’ kepada asal yang kemudian diamini oleh sebagian murid-muridnya.[63] Definisi ini walaupun tidak mendapat kritikan seperti definisi yang sudah-sudah dan benar bahwa proses yang terjadi tidak lebih dari yang telah disebutkan namun definisi yang dibawakan masih terlalu umum.
Akhund Khurasani setelah mengajukan keberatan terhadap definisi yang menambahkan kata zhan mengajukan definisinya sendiri:
“Ijtihad adalah mengusahakan segala kemampuan untuk menghasilkan hujjah atas hukum syar’i”[65]
Akhund Khurasani lebih memilih kata hujjah dikarenakan tolok ukur kesahihan sebuah amal perbuatan seorang muslim adalah mendapatkan dan adanya hujjah bagi dirinya. Penggunaan kata hujjah sendiri mencakup dalil-dalil yang masih belum sampai pada taraf ilmu seperti adanya sebuah hadis ahad yang sahih dan juga mencakup ilmu/keyakinan seseorang tentang sebuah dalil semisal al-Quran. Dengan ibarat khas ilmuwan usul fikih kata hujjah mencakup ‘ilmu’ dan ‘ilmi’. ‘Ilmu’ lebih diartikan dengan pengetahuan yang disertai dalil-dalil yang pasti, sementara ‘ilmi’ adalah pengetahuan yang tidak disertai oleh dalil-dalil yang pasti (zhan), namun oleh Allah dinaikkan nilainya seperti sebuah dalil yang pasti. Dan hal itu berlaku seperti pada hadis ahad yang sahih. Hadis ahad bukan dalil yang pasti yang dapat mendatangkan keyakinan kepada seseorang, tidak seperti hadis mutawatir, namun memberikan sebuah persangkaan yang lebih tentang sesuatu yang dikabarkannya. Persangkaan yang sebelumnya dalam ayat al-Quran surat Yunus ayat 36 dianggap tidak berarti untuk mencapai kebenaran dan dengan bantuan ayat-ayat lain terkait dengan masalah tersebut hadis ahad dapat diamalkan.
Pekerjaan rumah yang masih tertinggal dalam definisi ini adalah seorang mujtahid dalam proses penyimpulan hukumnya tidak hanya menghasilkan hukum syar’i. Hal itu lebih disebabkan karena pada kondisi-kondisi tertentu terkait dengan sebuah obyek masalah tidak ditemukan teks yang menjelaskan masalah yang dihadapi. Dalam khazanah usul fikih Syiah kumpulan hukum-hukum ini disebut ‘Ashl ‘Amali’ (prinsip praktis). Artinya, ketika tidak ditemukan sebuah dalil atau lebih lewat teks, seorang fakih atau mujtahid tetap bertanggung jawab untuk menyimpulkan sebuah hukum karena bagaimanapun setiap perilaku seorang mukallaf harus berlandaskan argumentasi. Ketiadaan hukum syar’i menuntut seorang fakih untuk menyimpulkan sebuah hukum sebagai sikap praktis karena ketiadaan teks yang sesuai dengan masalah yang dihadapi dan di sisi lain perilakunya harus berlandaskan dalil atau hujjah.
Mungkin Akhund Khurasani masih berkelit bahwa penggunaan kata hukum syar’i yang disebutkan telah mencakup juga makna prinsip praktis karena ketiadaan hukum syar’i. Namun, melihat keduanya, hukum syariat dan prinsip praktis, berbeda secara substansial maka penyebutannya menjadi sebuah keharusan.
Dari sini, untuk menghilangkan kritikan selanjutnya yang dihadapi oleh Akhund Khurasani, Sayyid Khu’i dalam bukunya ar-Ra’yu as-Sadid fi al-Ijtihad wa at-Taqlid secara transparan menambahkan prinsip praktis tersebut. Beliau mendefinisikan ijtihad sebagai berikut 
“Ijtihad adalah berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan hujjah atas realita (waqi’i) dan atau atas tanggung jawab praktis lahiri (zhahiri)”.[66]
Kata realita (waqi’i) dan lahiri (zhahiri) merujuk pada pembagian hukum menjadi dua bagian; waqi’i dan zhahiri. Hukum waqi’i adalah hukum yang jelas dan tidak memiliki keraguan terkait dengan obyeknya. Sementara hukum zhahiri adalah hukum yang terkait dengan obyek yang masih ragu. Hukum waqi’i seperti ayat yang mewajibkan haji. Obyek hukum adalah haji dan hukumnya pasti yaitu wajib bagi orang yang mampu. Sementara contoh hukum zhahiri seperti keraguan terhadap pakaian yang najis. Hukumnya adalah pakaian tersebut tidak najis karena dalil yang ada menyebutkan bahwa perlakukan segala sesuatu seperti suci sehingga suatu ketika engkau mendapatinya najis.[67]
Definisi yang diajukan oleh Sayyid Khu’i telah berhasil menyelesaikan perbedaan dalam usaha mendefinisikan kata ijtihad dengan maknanya yang umum. Setelah beliau, ulama Syiah saat ini dalam mendefinisikan kata ijtihad makna umum lebih memilih pendapat beliau.
Penutup
Dengan mempelajari secara seksama perkembangan sejarah makna ijtihad, makna khusus dan makna umum, terlihat perbedaan substansial. Makna pertama memberikan otoritas penuh kepada seorang mujtahid untuk menyimpulkan sebuah hukum yang pada akhirnya mendudukkan ijtihad sebagai salah satu sumber hukum. Tentunya pemahaman ini tanpa melupakan sebuah kenyataan lain bahwa itu dilakukan ketika ketiadaan nas dan teks. Sementara makna kedua, murni sebuah proses kerja ilmiah untuk menyimpulkan sebuah hukum syariat. Ijtihad dalam konteks ini bukan sumber hukum syariat dan tidak akan pernah menjadi sumber hukum syariat.
Ijtihad dengan makna khusus, dalam Syiah, menjadi terlarang, haram sementara ijtihad dengan makna umum merupakan keharusan.